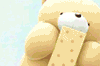Cerita Sahabat Getaran. Disusul dengan potongan lagu Built to Last-nya Meleè, menandakan sebuah SMS masuk.Aku berjalan menuju arah meja belajarku dan meraih ponsel yang sedang di-charge. Tidak ada firasat sama sekali, tidak ada pikiran negatif sama sekali. Kemudian kubaca SMS itu: Kar, ayahnya Didim meninggal. Dimakamkan di Solo hari ini.Sender: Dinda (+6285612069800)08:10 PM Meninggal? Ayah Didim meninggal?Selanjutnya, bagaikan kejapan mata, aku langsung menghubungi seluruh kawan-kawanku satu per satu, memberitahukan kabar meninggalnya ayah Didim. Tapi apa yang aku dapat bukanlah sesuatu yang aku harapkan.“Iya Kar, gue udah tahu. Kemarin malem meninggalnya,” ujar Bagas saat aku menghubunginya.“Ayah Didim emang udah sakit sejak awal semester ini, Kar. Sakit stroke, katanya.” Rizka berkata demikian saat aku meneleponnya.“Didim nggak masuk dari kemarin gara-gara harus ke Solo, Kar.” Dan itu adalah respon dari Reza, teman sekelasku yang terakhir kukabari.Aneh. Mengapa hanya aku seorang yang nampaknya belum tahu apa-apa akan masalah ini? Bahkan Bagas mengatakan bahwa ayah Didim meninggal kemarin malam. Ada apa ini? Semua orang sudah tahu tapi aku, yang merupakan sahabat Didim, menjadi orang terakhir yang tahu akan kabar ini?Seperti orang kerasukan, aku langsung mengetik SMS cepat-cepat kepada Didim. Terkirim. Tidak dibalas. Kukirim lagi untuk kedua kalinya. Tiga kali. Masih tidak dibalas. Aku telepon, kudengar nada tersambung, lalu terputus. Kucoba lagi, tapi tetap tidak dijawab.Didim masih sengaja tidak mau berkomunikasi denganku.Apa yang salah? Apa yang salah?! Rasanya aku ingin berteriak. Setelah nyaris satu semester ini ia menghindariku terus, ogah-ogahan berbicara denganku, bahkan sengaja menukar bangkunya sehingga tidak lagi bersebelahan denganku, ia masih tidak mau menghubungi aku di saat-saat seperti ini?Aku terpekur. Hampa. Saat itu, waktu bagai berputar balik. ***Dua tahun yang laluSemua berawal semenjak aku kelas 1 SMP. Masih tenggelam dalam euforia, aku menyongsong kelas baruku dengan penuh semangat. Yah... kamu juga pasti pernah merasakan itu, kan? Sindrom ‘mendadak-merasa-gede’ karena statusmu sekarang adalah anak putih-biru, bukan lagi putih-merah seperti dulu. Tapi euforiaku mendadak lenyap ketika setelah dua minggu masuk sekolah, rotasi bangku mengharuskanku duduk di deretan belakang, bersama seorang cowok berantakan yang kerjaannya hanya tidur saja di kelas. “Didim.” Sesingkat itulah ia memperkenalkan dirinya kepadaku. Nama lengkapnya Ardiko Dimas Syailendra, dan entah dari mana ia mendapatkan panggilan ‘Didim’ tersebut. Berantakan, itulah ciri khasnya. Pagi-pagi datang ke sekolah sudah dengan seragam yang keluar, sepatu diinjak, rambut mencuat-cuat tidak tersisir dan membawa barang seadanya. Kalau aku bilang ‘seadanya’, itu berarti benar-benar SEADANYA: cuma tas lusuh yang warnanya tidak jelas saking kotornya, berisi sebuah file catatan yang kertasnya nyaris kosong, satu bulpen, satu pensil, dompet dan ponsel. Berantakan, ‘hobi’ melawan peraturan, suka tidur di kelas dan tidak perduli dengan pelajaran—lengkap sudah semua alasan yang langsung membuat Didim menjadi musuh nomor satu semua guru. Baru sebulan masuk SMP, ia sudah dipanggil oleh Bu Ningrum, wali kelas kami saat itu, karena komplain dari guru-guru yang terus mengalir tentang tingkahnya yang tidak pantas. Tapi, di sinilah sebenarnya persahabatanku dengan Didim dimulai. Aku ingat hari itu, hari di mana sepulang sekolah Didim dipanggil Bu Ningrum untuk berbicara empat mata dengannya. Di tengah jalan pulang menuju gerbang, mendadak aku dicegat oleh Dinda—yang juga teman sekelasku—dan disuruh menemui Bu Ningrum di ruang guru. Aku sempat merasa bingung kenapa aku harus ikut dipanggil segala. Kalau Didim, aku maklum. Kalau aku, yang notabenenya termasuk anak ‘baik-baik’ di kelas, apa masalahnya? Semuanya langsung terjawab tatkala aku masuk dan duduk di samping Didim saat itu juga. “Sekar, ibu harap kamu bisa membantu Ardiko dalam pelajaran, ya.” “Sa-saya, bu?” Aku langsung tergagap karena kaget. Bu Ningrum mengangguk yakin. “Ibu lihat keseluruhan nilai kamu baik dan kamu rajin mengerjakan tugas. Ibu harap kamu bisa membantu Ardiko supaya nilai-nilainya bisa, ehm, terisi semua.” Terisi semua—itu artinya nilai Didim semuanya kosong. Untuk urusan pelajaran, Didim memang parah. Dua minggu sebangku dengannya, tak pernah kulihat ia mengumpulkan PR satu kali pun. Demikian juga saat ulangan, tahukah kalian apa yang ia lakukan? Tidur. Ia tidur bahkan saat sebelum soal dibagikan, dan ketika waktu ulangan selesai, ia dengan santainya mengumpulkan lembar jawaban yang tidak berisi jawaban itu. “Kamu bisa mengajari Ardiko kan, Sekar?” Suara Bu Ningrum menarikku kembali ke alam nyata. Kalau boleh jujur, rasanya aku malaaas sekali berurusan dengan manusia asal-asalan ini. Tapi, kurasa reaksi penolakanku kepada Bu Ningrum juga bukan merupakan tindakan yang bijaksana. Wali kelas mana sih, yang mau melihat anak didiknya gagal? Maka, dengan berat hati, aku pun mengangguk. ***Semenjak hari itu aku disuruh oleh Bu Ningrum untuk tetap duduk sebangku bersama Didim. Di saat anak-anak lain berpindah-pindah sesuai rotasi meja, aku tetap duduk di bangku yang sama, di baris belakang bersama Didim. Hari demi hari, minggu demi minggu, aku mengajari Didim semua materi pelajaran. Menyikutnya agar ia tetap terjaga saat guru sedang menerangkan di depan kelas. Memastikan bahwa lembar jawabannya terisi saat ulangan. Bahkan hingga mengirimi dia SMS setiap malam agar ia tidak lupa untuk membawa seluruh buku pelajaran sesuai jadwal, bukan hanya isi tas minimalisnya seperti yang dulu ia lakukan. Selama itu juga, aku mulai memahami karakternya. Didim bukan anak yang bodoh—sebaliknya, menurutku ia sangat pintar. Pada awalnya aku menduga bahwa mengajarinya materi pelajaran akan menuntutku kesabaran yang berlebih, tapi aku salah. Ia dengan cepat menyerap semua materi yang aku jelaskan, dan bahkan aku mulai ragu bahwa ia butuh seorang tutor sebaya untuk mengajarinya. Yang ia butuhkan hanya niat dan motivasi untuk bersekolah dengan benar. Berbagai pertanyaan mulai muncul di dalam benakku: mengapa anak sepintar dia sangat malas belajar? Mengapa ia selalu terlihat mengantuk sepanjang hari? Mengapa ia sampai tidak perduli dengan nilainya—bahkan sampai bisa cuek tidur saat ulangan? “Keluarga gue,” ujarnya mendadak suatu hari, tatkala aku meminjamkannya buku catatan biologi, “hmm, apa itu istilahnya? Ah, iya. Keluarga gue disfungsional.” Disfungsional. Bahkan pemilihan kata-katanya terlalu intelek untuk ukuran anak yang dicap ‘bodoh’. “Disfungsional gimana maksud lo?” tanyaku. “Gue bungsu dari dua bersaudara. Abang gue, umurnya sepuluh tahun lebih tua. Dia nggak pernah ada di rumah. Ada aja alasannya; nginep di rumah teman, lah, ngerjain tugas kuliah, lah...” Didim berhenti sejenak, seperti menimbang-nimbang apakah ia mau lanjut bercerita soal kehidupan pribadinya kepadaku. “Kalo abang gue aja umurnya udah segitu, lo kebayang lah umur orangtua gue seberapa. Bokap gue udah tua, tinggal nunggu beberapa tahun lagi buat pensiun, tapi dia gila kerja banget. Sedangkan nyokap...” Ia kembali terdiam. “Nyokap lo kenapa?” “Gue nggak akur sama nyokap.” Ia menghela napas. “Semenjak abang gue bertingkah kayak ‘anak hilang’ begitu, entah kenapa nyokap jadi suka paranoid sama gue. Gue pulang sore sedikit, pasti langsung dituduh macam-macam. Keluyuran lah, main-main lah, malah sampai menduga gue pemakai narkoba.” “Tapi, elo enggak...” aku terdiam sejenak, ragu ingin meneruskan, “...elo enggak pakai narkoba kan, Dim?” “Ya enggak, lah, Kar.” Didim malah tertawa kecil atas tuduhan itu. “Gue mungkin tidur nyaris setiap saat, tapi gue bukannya nge-fly atau high begitu.” “Terus, kenapa elo sering banget ketiduran di kelas?” “Karena gue memang selalu begadang.” Didim mulai membuka buku catatan biologiku dan menyalin isinya, seraya meneruskan, “Bokap gue pulang kerja di atas jam sepuluh malam hampir setiap hari. Nyokap, entah kenapa, selalu udah tidur saat itu. Aneh sih—bukannya biasanya istri selalu nungguin suaminya pulang kerja, ya? Tapi, ya begitulah nyokap gue. Akhirnya, gue lah yang selalu nungguin bokap pulang.” Mendadak aku merasa semua sikap Didim masuk akal. Keluarganya memang berantakan. Ayahnya yang bekerja terlalu keras hingga melupakan keluarganya, ibunya yang paranoid dan nampaknya juga kurang akur dengan ayahnya, hingga kakaknya yang tidak pernah ada di rumah. Wajar kalau Didim menjadi tidak termotivasi untuk sekolah, karena bahkan keluarganya pun tidak berada di belakangnya memberikan support. Dan ini juga membuktikan bahwa dugaanku benar; yang ia butuhkan bukanlah tutor, tapi semangat dan dukungan untuk berprestasi. “Dim,” aku memulai pembicaraan lagi, “elo jangan males-males sekolah, ya.” Didim menaikkan alis. “Kenapa?” “Yaaah... setidaknya, harus ada satu orang yang ‘bener’ lah di keluarga lo. Kalau abang lo nggak bisa, setidaknya ya elo.” Didim tidak merespon apa pun selain tersenyum tipis. Aku tidak ingat persisnya kapan penggalan dialog itu terjadi, tapi yang jelas, semenjak itu perlahan-lahan prestasi sekolah Didim berangsur-angsur membaik. Walau masih tetap dengan ciri khas penampilannya yang berantakan, tak pernah kulihat lagi ia tertidur saat pelajaran. Tugas dan PR selalu ia kumpulkan. Bahkan tak jarang, nilai ulangannya lebih tinggi dibanding nilai ulanganku. Saat kenaikan kelas, ia masuk sepuluh besar. Bu Ningrum tidak henti-hentinya berterimakasih kepadaku yang dianggapnya telah sukses membimbing Didim ke ‘jalan yang benar’. “Sekar,” panggilnya saat pembagian raport, seraya menatap papan tulis yang berisi daftar nama-nama siswa yang masuk sepuluh besar. “Ya?” responku, acuh tak acuh. “Semoga kelas dua kita sekelas lagi, ya.” Ia nyengir lebar. Aku terbengong-bengong. Sama sekali tak menyangka ia bisa berharap seperti itu. ***Aku tidak tahu ini kebetulan, takdir, atau apa, tapi yang jelas kelas dua aku satu kelas lagi dengan Didim. Dan walaupun sebenarnya masa ‘tutorial’-ku dengannya sudah berakhir—setidaknya saat ia menunjukkan peningkatan prestasi—kami akhirnya tetap duduk sebangku dan berteman dekat. Banyak orang-orang meledek kami dan menyebut kami berdua pacaran, tapi tidak, kami tidak berpacaran. Kami hanya bersahabat dekat, seperti kakak dan adik. Namun, di kelas tiga, mendadak semuanya berubah. Sangat berubah. Diawali dengan kesibukanku mengikuti seleksi olimpiade fisika di penghujung tahun keduaku, yang berarti agendaku akan terus dipenuhi dengan karantina dan lomba hingga akhir semester awal kelas tiga. Di saat-saat seperti itu aku mulai merasa bahwa pertemananku dengan Didim mulai berjarak. Walaupun masih tetap sekelas, namun frekuensi pertemuan kami di sekolah menurun drastis, mengingat hampir setiap hari aku terkena dispensasi untuk persiapan olimpiade. Kalau pun aku sedang masuk sekolah, entah mengapa Didim juga terkesan ogah-ogahan berbicara denganku. Rasanya hubungan kami kembali ke titik awal lagi, saat ia dan aku masih saling diam satu sama lain. Puncaknya, saat aku masuk sekolah setelah melalui seminggu masa karantina, aku menemukan bahwa Dinda lah yang mengisi posisi bangku di sampingku, bukan lagi Didim. Ia dengan seenaknya menyuruh Dinda bertukar posisi dengannya agar ia tidak lagi sebangku denganku. Marah, kesal, heran, semuanya bercampur menjadi satu saat itu. Tak tahan, aku mendampratnya saat istirahat makan siang. “Mau lo apa sih, Dim?” tanyaku tanpa basa-basi saat menemukan ia di kantin. Didim tidak menatapku, ia malah tetap fokus memakan mie ayamnya. “Didim!” Aku menggoyangkan bahunya, agak kasar. “Maksud lo apa? Tahu-tahu pindah kursi begitu?” Ia melirikku dengan tatapan terganggu. “Dua tahun kita duduk sebangku. Gue butuh variasi teman.” “Apa?” Aku tak bisa mempercayai pendengaranku saat itu. “Singkatnya, gue bosen aja sebangku terus sama elo, Sekar. Sesimpel itu.” Aku terlalu kaget untuk bisa bereaksi, sehingga aku sempat terdiam mematung selama beberapa detik. Mendadak sebuah logika sederhana terbentang di otakku: Didim ya tetap Didim. Seorang anak yang bandel, tidak perduli seberapa eratnya persahabatanku dengannya. Aku langsung balik badan dan berlari dari kantin. Berlari sejauh mungkin dari Didim, karena aku tidak ingin ia menyaksikan air mataku yang mulai tumpah. ***Kembali lagi ke hari ini. Sudah tiga hari Didim tidak masuk sekolah, dan sudah sehari semenjak SMS Dinda yang mengabari tentang meninggalnya ayah Didim. Walaupun hubungan kami sudah tidak seakrab dulu lagi, bohong kalau aku bilang aku tidak peduli dengan berita duka tersebut. Apalagi ini adalah ayahnya Didim. Ayah dari sahabatku—mantan sahabatku. Tapi, alangkah terkejutnya aku atas apa yang aku temukan di kelas yang masih kosong pagi ini. Ardiko Dimas Syailendra ada di kelas—dan ia duduk di sebelah bangkuku. “Didim?” tanyaku kaget. “Elo masuk? Kok elo pakai baju bebas?” Didim menatapku dengan tatapan sedih. “Gue bukan mau masuk sekolah, Kar. Gue mau pamitan sama mengurus surat pindah.” “Pi-pindah?” Aku tergagap. “Pindah ke mana?” “Ke Solo.” Telapak tanganku langsung terasa dingin saat mendengar itu. Namun, kebalikan dengan telapak tanganku yang dingin, aku merasa bahwa mataku mulai panas... dan berair. “Kenapa? Kok mendadak banget?” tanyaku, mulai dengan artikulasi terbata-bata karena menahan tangis. “Nggak mendadak, sebetulnya.” Pandangan mata Didim menerawang jauh. “Sebelumnya, gue mau minta maaf, Kar.” “Minta maaf?” “Iya. Karena sudah menyakiti lo waktu itu, waktu gue mendadak tukar bangku dengan Dinda. Tapi semua itu gue lakukan, karena gue nggak tahan harus dekat-dekat sama lo, saat gue bahkan nggak bisa cerita apa pun ke elo.” “Cerita apa? Apa yang selalu elo sembunyikan selama ini?” “Bokap divonis stroke semenjak awal kita masuk kelas tiga, Kar.” Didim berhenti sejenak, menghela napas, berat. “Itu sangat berat buat gue... buat keluarga gue. Elo tahu kan gimana kondisi keluarga gue. Abang gue masih tetap saja nggak pulang-pulang walau udah tahu bahwa bokap sakit. Nyokap juga bukannya berusaha tegar dan merawat bokap, tapi malah panik sendiri dan menambah keruh suasana. Praktis yang merawat bokap cuma gue dan paman gue, adiknya bokap.” Didim terdiam sejenak, seperti menahan emosinya. Hening menyelimuti kami berdua meski hanya sesaat. “Saat itu... gue ingin sekali cerita ke elo. Seperti waktu kelas satu, pertama kalinya gue cerita ke elo tentang kondisi keluarga gue yang berantakan. Tapi elo lagi sibuk dengan olimpiade fisika lo, dan elo kelihatan capek sekali dengan kegiatan itu. Makanya gue nggak cerita ke elo, gue takut menambah beban lo.” Pertahananku tumpas sudah. Air mata mulai jatuh membasahi pipiku. Sahabat macam apa aku ini? Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri. Aku bahkan berani menuduh Didim macam-macam saat ia mulai menjauh dariku. Aku ini benar-benar bodoh!Didim mengalihkan pandangannya ke lantai, menunduk. “Jangan nangis, Kar,” ujarnya pelan. “Elo nggak tahu seberapa besar rasa bersalah gue sama lo, jadi tolong, jangan nangis. Itu cuma membuat perasaan gue makin sedih.” “O-oke.” Tersendat-sendat, aku berusaha meredakan tangisku. “Ja-jadi... kenapa? Kenapa elo harus pindah?” “Pas bokap divonis sakit, keluarga gue makin nggak jelas. Abang yang nggak pulang-pulang, nyokap yang nggak bisa diandalkan, bokap yang kondisinya makin buruk dari hari ke hari... Akhirnya keluarga besar gue menimbang-nimbang bahwa gue pindah saja ke Solo, biar gue diasuh sama nenek gue di sana.” “Harus, ya?” Aku bertanya pelan, sakit. “Elo harus pindah?” Didim mengangguk lemah. “Sekarang bokap udah nggak ada, Kar. Keluarga gue udah benar-benar kehilangan ‘tiang’ penyangganya. Gue udah nggak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan di sini.” “Elo...” aku terdiam, kehabisan kata-kata. “Elo seharusnya cerita ke gue, bodoh.” Didim tersenyum pahit. “Lo nggak tahu betapa gue sangat berharap bahwa gue bisa cerita sama lo saat itu.” “Baik-baik ya di Solo.” Aku menepuk bahunya, rasa perih makin menjalar di hatiku. “Belajar yang rajin.” Ia mengangguk, kali tersenyum damai. “Iya. Kan udah ada yang memotivasi gue selama ini.” “Sering-sering kabar-kabarin gue, ya.” “Pasti.” Setelah itu Didim pergi meninggalkan kelas, menuju ruang TU untuk mengurus surat kepindahannya. Kembali lagi, aku terpekur hampa sendirian di kelas. Hari masih pagi, sekolah masih sepi. Tapi aku sudah menangis sendiri.
Senin, 17 Mei 2010
$@h@b@tt
Cerita Sahabat Getaran. Disusul dengan potongan lagu Built to Last-nya Meleè, menandakan sebuah SMS masuk.Aku berjalan menuju arah meja belajarku dan meraih ponsel yang sedang di-charge. Tidak ada firasat sama sekali, tidak ada pikiran negatif sama sekali. Kemudian kubaca SMS itu: Kar, ayahnya Didim meninggal. Dimakamkan di Solo hari ini.Sender: Dinda (+6285612069800)08:10 PM Meninggal? Ayah Didim meninggal?Selanjutnya, bagaikan kejapan mata, aku langsung menghubungi seluruh kawan-kawanku satu per satu, memberitahukan kabar meninggalnya ayah Didim. Tapi apa yang aku dapat bukanlah sesuatu yang aku harapkan.“Iya Kar, gue udah tahu. Kemarin malem meninggalnya,” ujar Bagas saat aku menghubunginya.“Ayah Didim emang udah sakit sejak awal semester ini, Kar. Sakit stroke, katanya.” Rizka berkata demikian saat aku meneleponnya.“Didim nggak masuk dari kemarin gara-gara harus ke Solo, Kar.” Dan itu adalah respon dari Reza, teman sekelasku yang terakhir kukabari.Aneh. Mengapa hanya aku seorang yang nampaknya belum tahu apa-apa akan masalah ini? Bahkan Bagas mengatakan bahwa ayah Didim meninggal kemarin malam. Ada apa ini? Semua orang sudah tahu tapi aku, yang merupakan sahabat Didim, menjadi orang terakhir yang tahu akan kabar ini?Seperti orang kerasukan, aku langsung mengetik SMS cepat-cepat kepada Didim. Terkirim. Tidak dibalas. Kukirim lagi untuk kedua kalinya. Tiga kali. Masih tidak dibalas. Aku telepon, kudengar nada tersambung, lalu terputus. Kucoba lagi, tapi tetap tidak dijawab.Didim masih sengaja tidak mau berkomunikasi denganku.Apa yang salah? Apa yang salah?! Rasanya aku ingin berteriak. Setelah nyaris satu semester ini ia menghindariku terus, ogah-ogahan berbicara denganku, bahkan sengaja menukar bangkunya sehingga tidak lagi bersebelahan denganku, ia masih tidak mau menghubungi aku di saat-saat seperti ini?Aku terpekur. Hampa. Saat itu, waktu bagai berputar balik. ***Dua tahun yang laluSemua berawal semenjak aku kelas 1 SMP. Masih tenggelam dalam euforia, aku menyongsong kelas baruku dengan penuh semangat. Yah... kamu juga pasti pernah merasakan itu, kan? Sindrom ‘mendadak-merasa-gede’ karena statusmu sekarang adalah anak putih-biru, bukan lagi putih-merah seperti dulu. Tapi euforiaku mendadak lenyap ketika setelah dua minggu masuk sekolah, rotasi bangku mengharuskanku duduk di deretan belakang, bersama seorang cowok berantakan yang kerjaannya hanya tidur saja di kelas. “Didim.” Sesingkat itulah ia memperkenalkan dirinya kepadaku. Nama lengkapnya Ardiko Dimas Syailendra, dan entah dari mana ia mendapatkan panggilan ‘Didim’ tersebut. Berantakan, itulah ciri khasnya. Pagi-pagi datang ke sekolah sudah dengan seragam yang keluar, sepatu diinjak, rambut mencuat-cuat tidak tersisir dan membawa barang seadanya. Kalau aku bilang ‘seadanya’, itu berarti benar-benar SEADANYA: cuma tas lusuh yang warnanya tidak jelas saking kotornya, berisi sebuah file catatan yang kertasnya nyaris kosong, satu bulpen, satu pensil, dompet dan ponsel. Berantakan, ‘hobi’ melawan peraturan, suka tidur di kelas dan tidak perduli dengan pelajaran—lengkap sudah semua alasan yang langsung membuat Didim menjadi musuh nomor satu semua guru. Baru sebulan masuk SMP, ia sudah dipanggil oleh Bu Ningrum, wali kelas kami saat itu, karena komplain dari guru-guru yang terus mengalir tentang tingkahnya yang tidak pantas. Tapi, di sinilah sebenarnya persahabatanku dengan Didim dimulai. Aku ingat hari itu, hari di mana sepulang sekolah Didim dipanggil Bu Ningrum untuk berbicara empat mata dengannya. Di tengah jalan pulang menuju gerbang, mendadak aku dicegat oleh Dinda—yang juga teman sekelasku—dan disuruh menemui Bu Ningrum di ruang guru. Aku sempat merasa bingung kenapa aku harus ikut dipanggil segala. Kalau Didim, aku maklum. Kalau aku, yang notabenenya termasuk anak ‘baik-baik’ di kelas, apa masalahnya? Semuanya langsung terjawab tatkala aku masuk dan duduk di samping Didim saat itu juga. “Sekar, ibu harap kamu bisa membantu Ardiko dalam pelajaran, ya.” “Sa-saya, bu?” Aku langsung tergagap karena kaget. Bu Ningrum mengangguk yakin. “Ibu lihat keseluruhan nilai kamu baik dan kamu rajin mengerjakan tugas. Ibu harap kamu bisa membantu Ardiko supaya nilai-nilainya bisa, ehm, terisi semua.” Terisi semua—itu artinya nilai Didim semuanya kosong. Untuk urusan pelajaran, Didim memang parah. Dua minggu sebangku dengannya, tak pernah kulihat ia mengumpulkan PR satu kali pun. Demikian juga saat ulangan, tahukah kalian apa yang ia lakukan? Tidur. Ia tidur bahkan saat sebelum soal dibagikan, dan ketika waktu ulangan selesai, ia dengan santainya mengumpulkan lembar jawaban yang tidak berisi jawaban itu. “Kamu bisa mengajari Ardiko kan, Sekar?” Suara Bu Ningrum menarikku kembali ke alam nyata. Kalau boleh jujur, rasanya aku malaaas sekali berurusan dengan manusia asal-asalan ini. Tapi, kurasa reaksi penolakanku kepada Bu Ningrum juga bukan merupakan tindakan yang bijaksana. Wali kelas mana sih, yang mau melihat anak didiknya gagal? Maka, dengan berat hati, aku pun mengangguk. ***Semenjak hari itu aku disuruh oleh Bu Ningrum untuk tetap duduk sebangku bersama Didim. Di saat anak-anak lain berpindah-pindah sesuai rotasi meja, aku tetap duduk di bangku yang sama, di baris belakang bersama Didim. Hari demi hari, minggu demi minggu, aku mengajari Didim semua materi pelajaran. Menyikutnya agar ia tetap terjaga saat guru sedang menerangkan di depan kelas. Memastikan bahwa lembar jawabannya terisi saat ulangan. Bahkan hingga mengirimi dia SMS setiap malam agar ia tidak lupa untuk membawa seluruh buku pelajaran sesuai jadwal, bukan hanya isi tas minimalisnya seperti yang dulu ia lakukan. Selama itu juga, aku mulai memahami karakternya. Didim bukan anak yang bodoh—sebaliknya, menurutku ia sangat pintar. Pada awalnya aku menduga bahwa mengajarinya materi pelajaran akan menuntutku kesabaran yang berlebih, tapi aku salah. Ia dengan cepat menyerap semua materi yang aku jelaskan, dan bahkan aku mulai ragu bahwa ia butuh seorang tutor sebaya untuk mengajarinya. Yang ia butuhkan hanya niat dan motivasi untuk bersekolah dengan benar. Berbagai pertanyaan mulai muncul di dalam benakku: mengapa anak sepintar dia sangat malas belajar? Mengapa ia selalu terlihat mengantuk sepanjang hari? Mengapa ia sampai tidak perduli dengan nilainya—bahkan sampai bisa cuek tidur saat ulangan? “Keluarga gue,” ujarnya mendadak suatu hari, tatkala aku meminjamkannya buku catatan biologi, “hmm, apa itu istilahnya? Ah, iya. Keluarga gue disfungsional.” Disfungsional. Bahkan pemilihan kata-katanya terlalu intelek untuk ukuran anak yang dicap ‘bodoh’. “Disfungsional gimana maksud lo?” tanyaku. “Gue bungsu dari dua bersaudara. Abang gue, umurnya sepuluh tahun lebih tua. Dia nggak pernah ada di rumah. Ada aja alasannya; nginep di rumah teman, lah, ngerjain tugas kuliah, lah...” Didim berhenti sejenak, seperti menimbang-nimbang apakah ia mau lanjut bercerita soal kehidupan pribadinya kepadaku. “Kalo abang gue aja umurnya udah segitu, lo kebayang lah umur orangtua gue seberapa. Bokap gue udah tua, tinggal nunggu beberapa tahun lagi buat pensiun, tapi dia gila kerja banget. Sedangkan nyokap...” Ia kembali terdiam. “Nyokap lo kenapa?” “Gue nggak akur sama nyokap.” Ia menghela napas. “Semenjak abang gue bertingkah kayak ‘anak hilang’ begitu, entah kenapa nyokap jadi suka paranoid sama gue. Gue pulang sore sedikit, pasti langsung dituduh macam-macam. Keluyuran lah, main-main lah, malah sampai menduga gue pemakai narkoba.” “Tapi, elo enggak...” aku terdiam sejenak, ragu ingin meneruskan, “...elo enggak pakai narkoba kan, Dim?” “Ya enggak, lah, Kar.” Didim malah tertawa kecil atas tuduhan itu. “Gue mungkin tidur nyaris setiap saat, tapi gue bukannya nge-fly atau high begitu.” “Terus, kenapa elo sering banget ketiduran di kelas?” “Karena gue memang selalu begadang.” Didim mulai membuka buku catatan biologiku dan menyalin isinya, seraya meneruskan, “Bokap gue pulang kerja di atas jam sepuluh malam hampir setiap hari. Nyokap, entah kenapa, selalu udah tidur saat itu. Aneh sih—bukannya biasanya istri selalu nungguin suaminya pulang kerja, ya? Tapi, ya begitulah nyokap gue. Akhirnya, gue lah yang selalu nungguin bokap pulang.” Mendadak aku merasa semua sikap Didim masuk akal. Keluarganya memang berantakan. Ayahnya yang bekerja terlalu keras hingga melupakan keluarganya, ibunya yang paranoid dan nampaknya juga kurang akur dengan ayahnya, hingga kakaknya yang tidak pernah ada di rumah. Wajar kalau Didim menjadi tidak termotivasi untuk sekolah, karena bahkan keluarganya pun tidak berada di belakangnya memberikan support. Dan ini juga membuktikan bahwa dugaanku benar; yang ia butuhkan bukanlah tutor, tapi semangat dan dukungan untuk berprestasi. “Dim,” aku memulai pembicaraan lagi, “elo jangan males-males sekolah, ya.” Didim menaikkan alis. “Kenapa?” “Yaaah... setidaknya, harus ada satu orang yang ‘bener’ lah di keluarga lo. Kalau abang lo nggak bisa, setidaknya ya elo.” Didim tidak merespon apa pun selain tersenyum tipis. Aku tidak ingat persisnya kapan penggalan dialog itu terjadi, tapi yang jelas, semenjak itu perlahan-lahan prestasi sekolah Didim berangsur-angsur membaik. Walau masih tetap dengan ciri khas penampilannya yang berantakan, tak pernah kulihat lagi ia tertidur saat pelajaran. Tugas dan PR selalu ia kumpulkan. Bahkan tak jarang, nilai ulangannya lebih tinggi dibanding nilai ulanganku. Saat kenaikan kelas, ia masuk sepuluh besar. Bu Ningrum tidak henti-hentinya berterimakasih kepadaku yang dianggapnya telah sukses membimbing Didim ke ‘jalan yang benar’. “Sekar,” panggilnya saat pembagian raport, seraya menatap papan tulis yang berisi daftar nama-nama siswa yang masuk sepuluh besar. “Ya?” responku, acuh tak acuh. “Semoga kelas dua kita sekelas lagi, ya.” Ia nyengir lebar. Aku terbengong-bengong. Sama sekali tak menyangka ia bisa berharap seperti itu. ***Aku tidak tahu ini kebetulan, takdir, atau apa, tapi yang jelas kelas dua aku satu kelas lagi dengan Didim. Dan walaupun sebenarnya masa ‘tutorial’-ku dengannya sudah berakhir—setidaknya saat ia menunjukkan peningkatan prestasi—kami akhirnya tetap duduk sebangku dan berteman dekat. Banyak orang-orang meledek kami dan menyebut kami berdua pacaran, tapi tidak, kami tidak berpacaran. Kami hanya bersahabat dekat, seperti kakak dan adik. Namun, di kelas tiga, mendadak semuanya berubah. Sangat berubah. Diawali dengan kesibukanku mengikuti seleksi olimpiade fisika di penghujung tahun keduaku, yang berarti agendaku akan terus dipenuhi dengan karantina dan lomba hingga akhir semester awal kelas tiga. Di saat-saat seperti itu aku mulai merasa bahwa pertemananku dengan Didim mulai berjarak. Walaupun masih tetap sekelas, namun frekuensi pertemuan kami di sekolah menurun drastis, mengingat hampir setiap hari aku terkena dispensasi untuk persiapan olimpiade. Kalau pun aku sedang masuk sekolah, entah mengapa Didim juga terkesan ogah-ogahan berbicara denganku. Rasanya hubungan kami kembali ke titik awal lagi, saat ia dan aku masih saling diam satu sama lain. Puncaknya, saat aku masuk sekolah setelah melalui seminggu masa karantina, aku menemukan bahwa Dinda lah yang mengisi posisi bangku di sampingku, bukan lagi Didim. Ia dengan seenaknya menyuruh Dinda bertukar posisi dengannya agar ia tidak lagi sebangku denganku. Marah, kesal, heran, semuanya bercampur menjadi satu saat itu. Tak tahan, aku mendampratnya saat istirahat makan siang. “Mau lo apa sih, Dim?” tanyaku tanpa basa-basi saat menemukan ia di kantin. Didim tidak menatapku, ia malah tetap fokus memakan mie ayamnya. “Didim!” Aku menggoyangkan bahunya, agak kasar. “Maksud lo apa? Tahu-tahu pindah kursi begitu?” Ia melirikku dengan tatapan terganggu. “Dua tahun kita duduk sebangku. Gue butuh variasi teman.” “Apa?” Aku tak bisa mempercayai pendengaranku saat itu. “Singkatnya, gue bosen aja sebangku terus sama elo, Sekar. Sesimpel itu.” Aku terlalu kaget untuk bisa bereaksi, sehingga aku sempat terdiam mematung selama beberapa detik. Mendadak sebuah logika sederhana terbentang di otakku: Didim ya tetap Didim. Seorang anak yang bandel, tidak perduli seberapa eratnya persahabatanku dengannya. Aku langsung balik badan dan berlari dari kantin. Berlari sejauh mungkin dari Didim, karena aku tidak ingin ia menyaksikan air mataku yang mulai tumpah. ***Kembali lagi ke hari ini. Sudah tiga hari Didim tidak masuk sekolah, dan sudah sehari semenjak SMS Dinda yang mengabari tentang meninggalnya ayah Didim. Walaupun hubungan kami sudah tidak seakrab dulu lagi, bohong kalau aku bilang aku tidak peduli dengan berita duka tersebut. Apalagi ini adalah ayahnya Didim. Ayah dari sahabatku—mantan sahabatku. Tapi, alangkah terkejutnya aku atas apa yang aku temukan di kelas yang masih kosong pagi ini. Ardiko Dimas Syailendra ada di kelas—dan ia duduk di sebelah bangkuku. “Didim?” tanyaku kaget. “Elo masuk? Kok elo pakai baju bebas?” Didim menatapku dengan tatapan sedih. “Gue bukan mau masuk sekolah, Kar. Gue mau pamitan sama mengurus surat pindah.” “Pi-pindah?” Aku tergagap. “Pindah ke mana?” “Ke Solo.” Telapak tanganku langsung terasa dingin saat mendengar itu. Namun, kebalikan dengan telapak tanganku yang dingin, aku merasa bahwa mataku mulai panas... dan berair. “Kenapa? Kok mendadak banget?” tanyaku, mulai dengan artikulasi terbata-bata karena menahan tangis. “Nggak mendadak, sebetulnya.” Pandangan mata Didim menerawang jauh. “Sebelumnya, gue mau minta maaf, Kar.” “Minta maaf?” “Iya. Karena sudah menyakiti lo waktu itu, waktu gue mendadak tukar bangku dengan Dinda. Tapi semua itu gue lakukan, karena gue nggak tahan harus dekat-dekat sama lo, saat gue bahkan nggak bisa cerita apa pun ke elo.” “Cerita apa? Apa yang selalu elo sembunyikan selama ini?” “Bokap divonis stroke semenjak awal kita masuk kelas tiga, Kar.” Didim berhenti sejenak, menghela napas, berat. “Itu sangat berat buat gue... buat keluarga gue. Elo tahu kan gimana kondisi keluarga gue. Abang gue masih tetap saja nggak pulang-pulang walau udah tahu bahwa bokap sakit. Nyokap juga bukannya berusaha tegar dan merawat bokap, tapi malah panik sendiri dan menambah keruh suasana. Praktis yang merawat bokap cuma gue dan paman gue, adiknya bokap.” Didim terdiam sejenak, seperti menahan emosinya. Hening menyelimuti kami berdua meski hanya sesaat. “Saat itu... gue ingin sekali cerita ke elo. Seperti waktu kelas satu, pertama kalinya gue cerita ke elo tentang kondisi keluarga gue yang berantakan. Tapi elo lagi sibuk dengan olimpiade fisika lo, dan elo kelihatan capek sekali dengan kegiatan itu. Makanya gue nggak cerita ke elo, gue takut menambah beban lo.” Pertahananku tumpas sudah. Air mata mulai jatuh membasahi pipiku. Sahabat macam apa aku ini? Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri. Aku bahkan berani menuduh Didim macam-macam saat ia mulai menjauh dariku. Aku ini benar-benar bodoh!Didim mengalihkan pandangannya ke lantai, menunduk. “Jangan nangis, Kar,” ujarnya pelan. “Elo nggak tahu seberapa besar rasa bersalah gue sama lo, jadi tolong, jangan nangis. Itu cuma membuat perasaan gue makin sedih.” “O-oke.” Tersendat-sendat, aku berusaha meredakan tangisku. “Ja-jadi... kenapa? Kenapa elo harus pindah?” “Pas bokap divonis sakit, keluarga gue makin nggak jelas. Abang yang nggak pulang-pulang, nyokap yang nggak bisa diandalkan, bokap yang kondisinya makin buruk dari hari ke hari... Akhirnya keluarga besar gue menimbang-nimbang bahwa gue pindah saja ke Solo, biar gue diasuh sama nenek gue di sana.” “Harus, ya?” Aku bertanya pelan, sakit. “Elo harus pindah?” Didim mengangguk lemah. “Sekarang bokap udah nggak ada, Kar. Keluarga gue udah benar-benar kehilangan ‘tiang’ penyangganya. Gue udah nggak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan di sini.” “Elo...” aku terdiam, kehabisan kata-kata. “Elo seharusnya cerita ke gue, bodoh.” Didim tersenyum pahit. “Lo nggak tahu betapa gue sangat berharap bahwa gue bisa cerita sama lo saat itu.” “Baik-baik ya di Solo.” Aku menepuk bahunya, rasa perih makin menjalar di hatiku. “Belajar yang rajin.” Ia mengangguk, kali tersenyum damai. “Iya. Kan udah ada yang memotivasi gue selama ini.” “Sering-sering kabar-kabarin gue, ya.” “Pasti.” Setelah itu Didim pergi meninggalkan kelas, menuju ruang TU untuk mengurus surat kepindahannya. Kembali lagi, aku terpekur hampa sendirian di kelas. Hari masih pagi, sekolah masih sepi. Tapi aku sudah menangis sendiri.
Diposting oleh C4NC3RZ di 06.29 0 komentar
Rabu, 14 April 2010
@rti Cinta Dalam Hiduupp
Mereka yang tidak menyukainya menyebutnya tanggung jawab.Mereka yang bermain dengannya, menyebutnya sebuah permainan.Mereka yang tidak memilikinya, menyebutnya sebuah impian.Mereka yang mencintai, menyebutnya takdir.Tuhan mengetahui yang terbaik, kadang akan memberi kesusahan untuk menguji kita. Kadang Ia pun melukai hati, supaya hikmat-Nya bisa tertanam dalam.Jika kita kehilangan cinta, maka pasti ada alasan di baliknya. Alasan yang kadang sulit untuk dimengerti, namun kita tetap harus percaya bahwa ketika Ia mengambil sesuatu, Ia telah siap memberi yang lebih baik.Mengapa menunggu?Karena walaupun kita ingin mengambil keputusan, kita tidak ingin tergesa-gesa.Karena walaupun kita ingin cepat-cepat, kita tidak ingin sembrono.Karena walaupun kita ingin segera menemukan orang yang kita cintai, kita tidak ingin kehilangan jati diri kita dalam proses pencarian itu.Jika ingin berlari, belajarlah berjalan duhulu.Jika ingin berenang, belajarlah mengapung dahulu.Jika ingin dicintai, belajarlah mencintai dahulu.Pada akhirnya, lebih baik menunggu orang yang kita inginkan, ketimbang memilih apa yang ada.Tetap lebih baik menunggu orang yang kita cintai, ketimbang memuaskan diri dengan apa yang ada.Tetap lebih baik menunggu orang yang tepat, karena hidup ini terlampau singkat untuk dilewatkan bersama pilihan yang salah, karena menunggu mempunyai tujuan yang mulia dan misterius.Perlu diketahui bahwa Bunga tidak mekar dalam waktu semalam,Kota Roma tidak dibangun dalam sehari,Kehidupan dirajut dalam rahim selama sembilan bulan,Cinta yang agung terus tumbuh selama kehidupan.Kebanyakan hal yang indah dalam hidup memerlukan waktu yang lama dan penantian kita tidaklah sia-sia.Walaupun menunggu membutuhkan banyak hal - iman, keberanian, dan pengharapan - penantian menjanjikan satu hal yang tidak dapat seorangpun bayangkan.Pada akhirnya, Tuhan dalam segala hikmat-Nya, meminta kita menunggu, karena alasan yang penting.
.... Cinta adalah memberi apa yang dunia tidak bisa beri.Dan keputusan menerima cinta itu sendiri melibatkan Tuhan di dalamnya, karena hanya Dia yang tahu apa yang terbaik buat kita, walau terkadang kita terlalu pintar untuk memaksakan kehendak bahwa apa yang kita rasa sudah benar dibandingkan dengan apa yang Tuhan pikirkan yang terbaik buat kita.Cinta sejati akan datang, di saat kita tidak pernah menduga sebelumnya, bahkan menggantikan semua rasa sakit karena cinta sesaat.Dan jangan kita terlalu bersedih karena kehilangan cinta 'YANG BAIK' kita, karena biasanya 'YANG BAIK' selalu mendahului yang "TERBAIK" dan Tuhan memberikan orang yang terbaik yang mencintai kita dan untuk kita cintai tepat pada waktunya.
Diposting oleh C4NC3RZ di 00.25 0 komentar